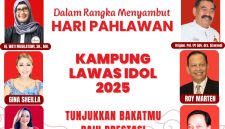Penulis: Dr. H. J. Faisal | Director of Logos Institute for Education and Sociology Studies (LIESS) / Pemerhati Pendidikan dan Sosial/ Anggota PJMI
ETNIKOM.NET, JAKARTA – Sambil menyeruput kopi hitam ditemani lagu Iwan Fals berjudul Doa Sang Pengobral Dosa, saya membaca berita tentang Sekolah Rakyat yang belakangan ramai dibicarakan.
Lagu lamal yang saya dengarkan sejak masih “imut-imut” dulu, tetap terasa relevan di usia saya yang kini hampir setengah abad. Liriknya tak hanya tajam, tapi juga menyentuh nurani sosial saya—dan mungkin juga Anda.
Lagu itu menggambarkan potret getir seorang perempuan yang hidup di pinggir peradaban—seorang pelacur tua yang berharap anak-anaknya tetap bisa makan dan punya masa depan. Ia bukan sekadar pekerja malam, tapi simbol perjuangan kelas bawah yang tetap menyimpan mimpi anak-anaknya menjadi manusia cerdas dan bermartabat.
Ia berdoa, dalam sunyi, di sela kegelisahan… “Oh Tuhan beri setetes rezeki, beri terang jalan anak hamba…”
Seketika pikiran saya tertuju pada Sekolah Rakyat, yang katanya ditujukan untuk anak-anak dari keluarga miskin ekstrem. Apakah ini betul solusi dari kegelisahan panjang para ibu di pinggir kehidupan itu—atau hanya kebijakan populis tanpa kajian akademis yang memadai?
Dua Panggung, Satu Drama: Sekolah Rakyat dan Program Makan Bergizi (MBG)
Di satu panggung, Sekolah Rakyat tampil bak bintang baru yang belum sempat latihan. Di sisi lain, program MBG (Makan Bergizi Gratis), yang digagas dengan anggaran hingga Rp171 triliun, mulai kehilangan penonton—dengan dapur belum matang dan jadwal makan hanya seminggu sekali.
Sekolah Rakyat hadir sebagai “alternatif pendidikan” yang diklaim lebih membumi, tetapi justru berpotensi membelah sistem pendidikan formal dan menciptakan kelas sosial baru. Jika MBG adalah dapur yang belum matang, maka Sekolah Rakyat adalah kelas tanpa kurikulum.
Keduanya lahir dari niat baik. Tapi niat tanpa kajian, tanpa partisipasi publik, dan tanpa roadmap yang jelas, hanya akan melahirkan kebijakan simbolik—bukan solusi substantif.
Mimpi Pendidikan Inklusif vs Imajinasi Populis
Sekolah Rakyat disebut-sebut sebagai solusi untuk anak-anak dari keluarga miskin ekstrem. Tapi pertanyaannya: Apakah ia lahir dari kebutuhan riil, atau hanya dari dorongan untuk terlihat revolusioner?
Bagi saya, kebijakan ini seperti sate lilit Bali: aromanya menggoda, tapi komposisinya belum jelas. Tak ada riset publik yang menjelaskan efektivitasnya. Tak ada kutipan dari pakar pendidikan. Tak ada pemetaan lokal. Rasanya lebih seperti obrolan antar tim sukses, bukan hasil forum ilmiah.
Pendidikan inklusif yang diperjuangkan dengan darah para pejuang pendidikan, air mata guru honorer, dan jurnal ilmiah para akademisi, tiba-tiba dipojokkan oleh program populis berlabel “rakyat”.
Hebatnya, istilah “rakyat” selalu punya daya magis. Ia memoles kebijakan setengah matang menjadi seolah-olah visioner. Tapi bila dikupas, kita hanya melihat strategi tanpa struktur, dan niat baik yang belum tentu berpihak.
Pasal 34: Dibaca Tapi Tak Diingat
Konstitusi seharusnya jadi kitab suci kebijakan publik. Pasal 34 UUD 1945 menyatakan: “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara.”
Sayangnya, dalam praktik, pemeliharaan itu justru diartikan sebagai pemisahan. Maka lahirlah Sekolah Rakyat—sebuah cadangan pendidikan yang ironisnya disiapkan hanya untuk mereka yang dianggap “tidak cukup layak” untuk sistem formal.
Pendidikan bukanlah sekadar bantuan sosial. Ia adalah amanat konstitusi. Dan anak-anak miskin tidak seharusnya diarahkan ke jalur alternatif yang tidak diakui akreditasi dan masa depannya. Mereka berhak atas pendidikan formal yang setara dan berkualitas—seperti anak-anak pejabat yang belajar di ruang ber-AC.
Dari Rapat ke Lapangan, Tanpa Transit di Perpustakaan
Kebijakan pendidikan idealnya lahir dari riset, uji coba, diskusi akademik, baru kemudian implementasi. Tapi di Indonesia, kita sering melewatkan itu semua. Dari rapat terbatas langsung konferensi pers, seperti pengiriman makanan lewat aplikasi online.
Sekolah Rakyat tampil terlalu percaya diri. Tanpa rujukan ilmiah, tanpa data empiris, tanpa jawaban atas pertanyaan metodologis dasar: “Pakai pendekatan apa?” atau “Mana hasil studinya?”
Jawaban sederhananya: mungkin pemerintah lebih rajin membaca polling elektoral ketimbang jurnal ilmiah. Karena dalam logika politik hari ini, viral lebih penting daripada valid.
Solusi atau Diskriminasi Struktural Baru?
Kehadiran Sekolah Rakyat yang dikelola Kemensos, bukan Kemendikbudristek, menunjukkan arah pendidikan yang melenceng dari ranah pedagogis ke ranah sosial.
Akibatnya bisa serius: orientasi pendidikan bisa bergeser dari pengembangan intelektual ke penanganan sosial. Kurikulum mungkin akan fokus pada keterampilan hidup dan nasionalisme, tapi minim pada penguasaan akademik.
Anak-anak miskin yang cerdas bisa jadi terjebak dalam jalur pendidikan yang tak punya akreditasi. Mereka kehilangan peluang untuk mobilitas sosial karena kebijakan negara memisahkan mereka dari sistem utama.
Lebih parah, siapa yang akan mengajar di sana? Guru dengan pelatihan pedagogis yang matang, atau relawan yang bermodal niat baik? Jika kualitas guru adalah lotere, maka masa depan murid pun menjadi taruhan.
Jika Negara Masih Ingat Pasal 34, Ini Solusinya
Sekolah Rakyat sudah berdiri, baliho sudah naik. Tapi apakah program ini menjamin masa depan atau hanya headline musiman?
Inilah yang seharusnya dilakukan negara:
1. Hentikan penciptaan jalur alternatif.
Bangun sistem pendidikan formal yang inklusif dan kuat. Jika rumah bocor, tambal atapnya—bukan bangun gubuk darurat di sampingnya.
2. Biayai penuh pendidikan anak-anak miskin. Mulai dari SPP, seragam, transportasi, hingga buku dan ekstrakurikuler. Jangan berharap anak miskin jadi Einstein hanya karena diberi sepatu gratis.
3. Perkuat daya tampung sekolah formal.
Latih guru, siapkan sistem pendukung, dan buat kebijakan penerimaan yang adil bagi semua latar belakang.
4. Buat kebijakan berbasis data dan kajian ilmiah. Libatkan akademisi, peneliti, dan masyarakat dalam menyusun kebijakan. Hentikan praktik politik pencitraan lewat jargon pendidikan.
Pendidikan, Hak Bukan Hadiah
Pendidikan adalah hak konstitusional, bukan hadiah dari penguasa. Ia bukan alat politik, bukan pula instrumen pansos. Jika negara ingin membela rakyat, maka perjuangkan hak pendidikan yang setara—bukan sekadar program darurat yang miskin arah.
Karena seperti doa sang pengobral dosa, anak-anak miskin pun terus berdoa. Tapi doa saja tak cukup. Mereka butuh negara yang hadir—bukan hanya di baliho dan pidato, tapi juga di ruang kelas yang setara dan bermutu.[]